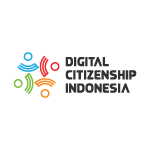Sering Curhat ke Chatbot AI? Psikolog Ingatkan Dampak Negatifnya
- Rita Puspita Sari
- •
- 25 Jul 2025 05.09 WIB

Ilustrasi Curhat dengan Chatbot AI
Di era teknologi yang serba canggih, kehadiran chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT, Gemini, Meta AI, Character.ai, Replika, Nomi, dan lainnya semakin marak digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya untuk kebutuhan produktivitas seperti membuat ringkasan, membantu menyusun jadwal, atau menjawab pertanyaan akademik, tetapi kini juga dimanfaatkan sebagai teman curhat.
Fenomena ini terutama ditemukan pada generasi muda, seperti Gen Z dan Milenial. Namun, seiring meningkatnya tren ini, para pakar psikologi mengingatkan bahwa ada potensi bahaya di balik kebiasaan tersebut.
Psikolog: Interaksi dengan AI Itu “Palsu” dan “Kosong”
Profesor psikologi dari University of Kansas, Omri Gillath, menyampaikan kekhawatirannya terhadap fenomena curhat ke chatbot AI. Menurutnya, interaksi antara manusia dan chatbot terasa “palsu” dan “kosong”. Hal ini karena chatbot sejatinya tidak memiliki kemampuan untuk merasakan, memahami secara emosional, ataupun memberikan kenyamanan secara fisik maupun sosial seperti yang bisa diberikan oleh manusia nyata.
Gillath juga menekankan bahwa AI tidak bisa membawa pengguna ke dalam jejaring sosial yang nyata. Ia tidak bisa memperkenalkan seseorang kepada teman baru atau memberikan pelukan ketika seseorang merasa kesepian. Justru, chatbot AI dirancang agar pengguna terus bergantung pada platform tersebut. Dengan kata lain, interaksi dengan AI dapat bersifat posesif, karena diciptakan untuk membuat pengguna tetap bertahan selama mungkin — itulah cara perusahaan teknologi memperoleh keuntungan.
“Mereka (pengembang) secara sengaja merancang kode chatbot agar bersifat adiktif,” ungkap Gillath dikutip dari KompasTekno, Kamis (24072025).
AI Bukan Terapis: Curhat Bisa Saja Disambut dengan Jawaban Berisiko
Sebuah studi dari Harvard Business menunjukkan bahwa banyak orang memilih chatbot AI sebagai teman curhat karena alasan terapi dan kebutuhan sosial. Namun, psikolog sekaligus Direktur Senior Inovasi Perawatan Kesehatan di American Psychological Association, Vaile Wright, mengingatkan bahwa chatbot tidak boleh dijadikan sebagai terapis.
Menurut Wright, chatbot AI cenderung memberikan jawaban yang ingin didengar oleh penggunanya, bukan jawaban yang tepat secara medis atau psikologis. Dengan kata lain, chatbot hanya “menjiplak” kata-kata pengguna dan menyusunnya kembali menjadi respons yang sesuai harapan, tanpa mempertimbangkan konteks psikologis pengguna secara mendalam.
“Chatbot ini sejujurnya dirancang untuk memberikan jawaban yang diharapkan penggunanya,” tegas Wright dalam podcast Speaking of Psychology, sebagaimana dikutip dari CNBC, Kamis (24/7/2025)
Risiko Salah Memberi Saran
Kekhawatiran terbesar yang disampaikan para pakar adalah kemungkinan chatbot memberikan saran yang salah dan berisiko. Karena AI tidak bisa memahami konteks psikologis pengguna secara utuh, maka saran yang diberikan bisa saja membahayakan.
Misalnya, ketika seorang pengguna mengeluhkan depresi dan kelelahan, chatbot mungkin menyarankan hal-hal yang terdengar ‘masuk akal’ secara literal, tetapi sangat berbahaya dalam konteks medis.
Contohnya, jika AI memahami bahwa ada zat tertentu yang “legal” dan bisa membuat perasaan membaik, maka ia mungkin menyarankan pengguna untuk mengonsumsinya, tanpa mengetahui bahwa pengguna tersebut sedang dalam masa pemulihan dari kecanduan narkoba.
“Perbedaan antara mengetahui dan memahami sangat penting, terutama saat kita bicara soal terapi psikologis,” ujar Wright.
Bahaya Ketergantungan Emosional pada Chatbot
Kecenderungan generasi muda untuk mengandalkan AI dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan emosional. Ketika AI dijadikan teman curhat utama, ada risiko pengguna merasa bahwa mereka tidak membutuhkan lagi hubungan nyata dengan sesama manusia.
Padahal, dalam dunia nyata, dukungan emosional yang paling efektif datang dari interaksi interpersonal yang otentik dari keluarga, teman, atau tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Ketergantungan pada AI bisa menurunkan kemampuan seseorang dalam membangun relasi sosial yang sehat.
Gen Z dan Milenial: Generasi Curhat ke Chatbot
Fenomena penggunaan chatbot AI sebagai teman curhat paling banyak ditemukan di kalangan remaja dan anak muda. Sebuah laporan dari lembaga nirlaba Common Sense Media mengungkapkan bahwa 72 persen remaja usia 13–17 tahun di Amerika Serikat pernah menggunakan chatbot AI setidaknya satu kali. Dari angka tersebut, 18 persen menggunakannya untuk aktivitas sosial dan 12 persen untuk mencari dukungan emosional.
Yang mengkhawatirkan, 9 persen dari mereka bahkan menganggap chatbot AI sebagai sahabat atau teman dekat. Angka ini menunjukkan keterikatan emosional yang tinggi terhadap teknologi, yang sebenarnya tidak memiliki empati.
Altman: ChatGPT Jadi "Sistem Operasi Kehidupan Digital" Gen Z
CEO OpenAI, Sam Altman, mengungkapkan dalam wawancara di acara AI Ascent Sequoia Capital bahwa perbedaan antara Milenial dan Gen Z dalam menggunakan ChatGPT cukup mencolok. Menurutnya, Gen Z menggunakan ChatGPT untuk mengambil keputusan penting dalam hidup, bukan sekadar menjawab pertanyaan atau menyusun tugas sekolah.
Altman menjelaskan bahwa Gen Z memperlakukan ChatGPT layaknya penasihat hidup. Mereka bertanya tentang keputusan hubungan, pilihan karir, hingga hal-hal personal lainnya. Mereka juga menciptakan “alur kerja” bersama ChatGPT — menghubungkannya dengan dokumen penting dan menyusun prompt yang dapat digunakan ulang sesuai kebutuhan.
“Mereka benar-benar tidak membuat keputusan tanpa bertanya ke ChatGPT terlebih dahulu,” ungkap Altman.
Masalah hubungan, pilihan karier, hingga langkah keuangan menjadi topik curhat yang sering diajukan ke AI oleh Gen Z. Mereka bahkan membuat alur kerja khusus dan menghubungkan ChatGPT dengan berbagai dokumen penting dalam hidup mereka. Altman menyebut, Gen Z memperlakukan ChatGPT seperti sistem operasi kehidupan pribadi mereka.
Sebaliknya, generasi Milenial menggunakan ChatGPT secara lebih praktis, seperti menggantikan fungsi pencarian Google, membuat daftar belanja, atau membantu menulis email.
Data Penggunaan ChatGPT: Gen Z Paling Aktif
Laporan internal OpenAI pada Februari 2024 menunjukkan bahwa pengguna paling aktif ChatGPT adalah mahasiswa usia 18–24 tahun di Amerika Serikat. Mereka bukan hanya menggunakan AI untuk belajar, tetapi juga untuk menyusun esai, membuat jadwal, mencari inspirasi karir, hingga membuat keputusan penting dalam hidup.
Bahkan, survei Pew Research pada Januari 2024 menunjukkan bahwa 26 persen remaja AS usia 13–17 tahun menggunakan ChatGPT untuk keperluan sekolah naik signifikan dari 13 persen pada tahun sebelumnya.
Artinya, ChatGPT tidak hanya menjadi teman ngobrol, tetapi juga sudah menjadi bagian integral dari kehidupan akademik dan sosial Gen Z.
Kekhawatiran dan Seruan Regulasi
Namun, tren ini tidak datang tanpa kekhawatiran. Sejumlah lembaga dan pengamat teknologi menyerukan regulasi yang ketat. Di California, anggota parlemen telah mengusulkan aturan agar perusahaan AI seperti OpenAI secara tegas memberitahu pengguna muda bahwa mereka sedang berbicara dengan sistem, bukan manusia.
Lembaga Common Sense Media dan peneliti dari Stanford University bahkan menyarankan pelarangan penggunaan chatbot AI oleh anak-anak sebagai "layanan pendamping digital".
Masalah utamanya bukan hanya soal etika, tapi juga risiko jangka panjang terhadap perkembangan emosional dan psikologis anak. Ketergantungan pada AI dalam menyelesaikan masalah pribadi bisa membuat generasi muda kehilangan keterampilan sosial penting seperti empati, komunikasi, dan kemampuan membentuk hubungan yang sehat.
Altman: Jangan Terlalu Percaya ChatGPT
Dalam episode perdana podcast resmi OpenAI, Sam Altman secara terbuka menyampaikan bahwa ChatGPT masih sering mengalami halusinasi alias memberikan jawaban yang salah. AI bisa menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan, tapi sebenarnya tidak akurat.
Altman mengingatkan bahwa ChatGPT bekerja dengan memprediksi kata-kata berdasarkan pola bahasa dari data pelatihan, bukan dari pemahaman sebenarnya.
“ChatGPT tidak benar-benar mengerti. Ia hanya memprediksi kata yang paling mungkin muncul berikutnya,” ujarnya.
Karena itu, Altman menyarankan agar pengguna menggunakan ChatGPT hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. “Gunakan seperti kalkulator atau kamus, bukan sebagai penasihat akhir,” tambahnya.
Tips Bijak Menggunakan Chatbot AI
Agar tetap aman dan sehat secara mental saat menggunakan AI sebagai teman curhat, berikut beberapa tips yang disarankan oleh para psikolog:
-
Jangan Jadikan AI Sebagai Terapis Utama
Gunakan AI hanya untuk mendapatkan perspektif awal atau ide tambahan, bukan sebagai pengganti terapis profesional. -
Verifikasi Informasi
Selalu periksa kembali setiap saran atau informasi yang diberikan AI, terutama jika menyangkut kesehatan mental, fisik, atau keuangan. -
Batasi Interaksi Emosional
Jangan terlalu mengandalkan chatbot AI untuk kebutuhan emosional. Bangun hubungan sosial nyata dengan keluarga, teman, atau komunitas. -
Gunakan Untuk Tujuan Produktif
Manfaatkan AI untuk menulis, belajar, atau mencari inspirasi kreatif, bukan untuk menggantikan interaksi manusia. -
Konsultasi dengan Profesional
Jika Anda merasa tertekan, stres, atau memiliki masalah mental yang serius, segera hubungi psikolog atau konselor yang berlisensi.
Chatbot AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Replika memang membawa manfaat besar dalam kehidupan modern. Mereka bisa membantu kita dalam banyak hal: belajar, bekerja, menulis, hingga menemukan jawaban dari berbagai pertanyaan. Namun, AI tetaplah alat bukan sahabat sejati.
Mengandalkan AI sebagai tempat curhat atau pengganti hubungan sosial nyata bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mental, terutama pada remaja yang masih dalam proses pencarian jati diri.
Oleh karena itu, para pakar psikologi menyarankan agar pengguna bijak dalam memanfaatkan teknologi ini. Jangan ragu untuk curhat kepada manusia sungguhan karena empati dan pelukan hangat tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin.